Satu hari di bulan September.
Berapa banyak cerita yang bisa terbilang dalam hitungan hari? Dari sekian hal baru yang dirasakan masih sedikit yang bisa menjadi tulisan. Belum lagi menghadapi suhu 14 derajat setiap hari, pulang kuliah rasanya hanya ingin bersembunyi di balik selimut sambil melanjutkan marathon The News Season 1.
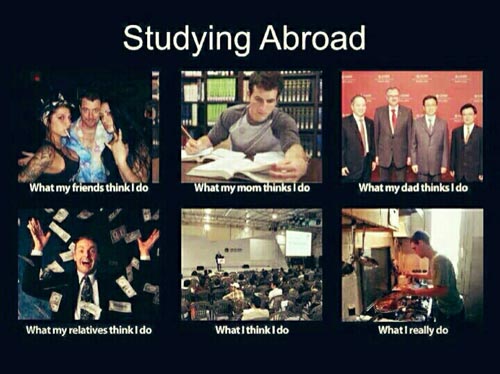
Tapi dari sekian banyak hari di bulan September yang semakin mendekati abu-abu, kemarin titik inferior semakin menjadi. Saya membutuhkan seseorang yang akrab, familiar dan bisa memberikan tawa lepas. Yang paling pasti, rasanya senang bisa berbahasa Indonesia, dan bahasa Makassar, tentu saja. Tiap hari harus mengerahkan otak untuk mentranslasi bahasa Inggris membuat otak menjadi sedikit berasap.
Siang tadi saya bercerita banyak dengan seorang sahabat. Bagaimana rasanya kelimpungan menerima sekian materi kuliah dalam waktu singkat.
“Saya berada dimana ketika mata kuliah dasar Jurnalistik?” *dikeplak*
Maklum saja, saya dulu tidak pernah terlalu serius menghadapi kuliah. Apalagi dengan semua jenis teori dasar. Ditambah dengan ke(sok)sibukan siaran di radio, membuat saya berpikir bahwa tataran teori hanya dipakai untuk hiasan belaka. Tidak perlulah menerapkan sejauh itu ilmu jurnalistik dalam tataran praktek.
Ketika pertanyaan mengapa memilih Public Relations, alasan pertama adalah karena kuliahnya lebih gampang –digampar anak PR–. Tetapi ketertarikan pada aspek jurnal ternyata tidak bisa hilang begitu saja. Beberapa mata kuliah praktik diambil sebagai pilihan. Jadilah saya anak PR dengan kebanyakan mata kuliah pilihan jurnalistik, dan tugas akhir dengan sudut pandang psikologi?
Halo apa kabar konsistensi?
Dalam sesi Jurnalisme dan Krisis Global entah mengapa pikiranku melayang ke 10 tahun yang lalu. Sebagian mencari sudut aman dan nyaman, memikirkan para rusher yang bisa dijadikan pelindung dan bisa dimintai pendapat kapanpun juga. Tapi kali ini berbeda, saya harus menjalani perang seorang diri.
Pertanyaannya, apakah saya tidak bisa mengikuti ritme kuliah?
2 minggu kuliah, dengan paper menyentuh 100 halaman yang harus dibaca plus hari senin sudah presentasi tugas pertama. Ya, shock lah! Tapi kebanyakan kekagetan masih kepada sistem belajar yang berbeda. 5 tahun meninggalkan bangku kuliah, dan harus membaca banyak hal dalam waktu bersamaan. Membiasakan diri dengan bahasa diskursus, hegemoni, McLuhan, dan sekian banyak istilah yang mestinya familiar dari jaman S1.
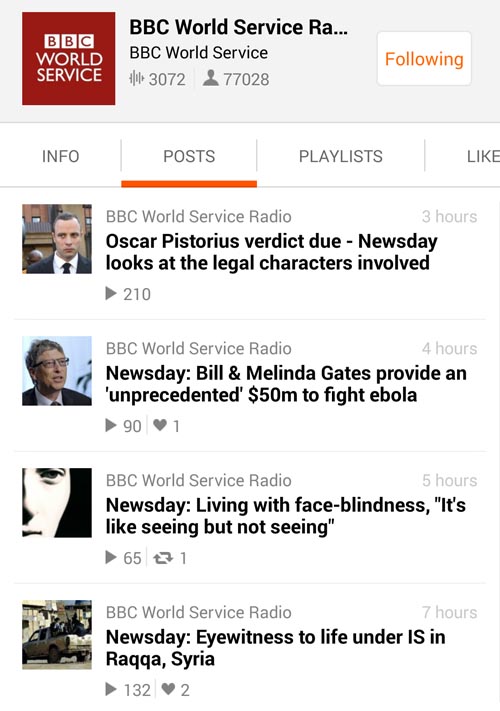
Tahukah kalian bahwa para warga dunia, Jerman, Rusia, Belgia, Swedia bisa membuatmu terlihat begitu inferior? Kadang perasaan malu untuk ikut berdiskusi karena takut terlihat bodoh—silly me—padahal Alexa, sang professor pembimbing kami sangat baik. Semuanya diakomodir untuk berpendapat. Cuma kadang, ketika sedang berbicara ada beban berat bahwa saya mewakili Negara Indonesia. Berjuang supaya tidak terlihat terlalu bodoh dan gugup.
Padahal berbicara sistem radio dan media, bolehlah ilmu kita diadu. Satu masalah penting adalah ketika mereka membicarakan konteks Eropa sebagai contoh, maka tinggallah saya mati gaya. Mecoba menghapal dan mengikuti sekian banyak peristiwa di Eropa, yang bagi mereka itu seperti bagian propinsi.
Ya iya lah. Kisruh pemerintahan, media dan politik di Negara sendiri juga belum beres, bagaimana ceritanya memperhatikan apa yang terjadi di Negara tetangga?
Tapi tentu saja tidak ada alasan untuk tidak mencari tahu. Untuk mata kuliah dasar di bulan pertama, kami belajar mengenai Global Media Communication. Bagaimana konteks media dan global menjadi satu frame, dengan semua implikasi dan konsekuensinya. Sesuatu yang sangat baru bagi saya–yang scope pergaulannya hanya mamakota—sekarang harus berkenalan dengan perdana menteri Inggris, partai Buruh di Scotland, kiprah ISIS, sampai kebijakan luar negeri Amerika.
Hahaha. Apa saya masih mempunyai alasan untuk mengeluh? Jujur, kadang perasaan capek lebih duluan melanda. Memikirkan bahan bacaan dan menjadikan ritme waktu yang berantakan. Bentuk penyangkalan seringkali dihabiskan dengan marathon serial The News Room dan House of Cards—hey ini ada hubungannya dengan jurnalistik!—atau hanya sekedar berjalan di dekat rumah.

Akhirnya satu hari di bulan September ini berakhir dengan banyak curhatan. Berharap dengan mengeluarkan sedikit uneg-uneg bisa membantu saya mengerti konsep globalisasi Berglers, ataupun Infotainment Politic yang dikemukakan oleh Cottle.
Menyesal? Jangan sampai perkataan itu keluar. Apapun jalan cerita atau episode setiap hari, masih jauh dari kata menyesal. Bukankah sudah panjang langkah untuk sampai ke Stockholm? Lagi pula menyerah tidak ada dalam kamus Tuan Beruang.
Selamat akhir pekan temans, 😉
3 thoughts on “Satu hari di bulan September.”
fighting Oppa!
Semangat lahh!!!
hahahaha… doakan rusher ini bisa menyusulmu segera…